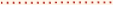PERKEMBANGAN SASTRA INDONESIA
DAN MULTIKULTURALISME *
OLEH : HERMAN J.WALUYO **
A.Pengantar
Sastra
Tanda-tanda zaman itu bias dikatakan berupa malapetaka yang mengancam peradaban, manusia, dan kemanusiaan jika tidak diungkapkan dan kemudian manusia lain yang berwenang menjawabnya kengan kebijakan politik, tindakan, atau pembinaan manusia lainnya. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sangat beraneka ragam yang bhineka (dan sejak tahun 1928 dinyatakan sebagai tunggal ika). Sifat bhineka itu adalah sifat das sein, sedangkan sifat tunggal ika adalah das sollen. Sebagai bangsa yang sangat aneka, kita selalu dalam proses tunggal ika bukan dalam arti monokultur dalam arti lebur menjadi satu, namun dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu, kita dapat bersatu padu dengan tetap menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan yang dimiliki. Bangsa
Seluruh bangsa pasti tahu bahwa perbedaan di antara bangsa
B. Multikulturalisme
Istilah multikulturalisme muncul sekitar tahun 1960-an di negara-negara Anglopone dalam kaitannya dengan migran-migran yang non-Eropah tentang bagaimana pilihan budaya mereka. Yang lebih popular saat ini adalah makna multikulturalisme dalam arti bagaimana Pemerintah atau kekuasaan yang dominant mengakomodasikan kepentingan dan suara race and etnicity yang dipandang minoritas. Akomodasi hak politik bagi golongan kecil yang tidak berdaya dipandang sebagai kebutuhan besar yang terpenting dari seluruh dunia. Corak dan bentuk multikulturalisme di setiap Negara berbeda tergantung dari kebutuhan budaya yang sangat majemuk itu (Tariq Modood,2009:1).
Sementara itu, Ainul Yaqin (2005) menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan suatu gerakan biologis untuk memahami segenap perbedaan yang ada pada diri setiap manusia serta bagaimana perbedaan itu dapat diterima sebagai hal yang alamiah dan tidak menjadi alas an bagi tindakan diskriminatif dengan sikap hidup yang cenderung dikuasai rasa irihati, dengki, dan buruk sangka. Ia menyatakan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan multikulturalisme dalam diri setiap anak didik dan pada gilirnnya pada seluruh warga Negara.
Perbedaan-perbedaan yang harus mendapat perhatian untuk tidak menimbulkan sikap dan perilaku yang antipati (tidak senang) adalah perbedaan: gender, klas sosial, bahasa, agama, usia, kemampuan/kecerdasan, etnis (kesukuan), dan kecacatan fisik/mental (difabel) (Ainul: 101 – 253). Dalam pembinaan multikulturalisme disadarkan kepada semua orang bahwa perbedaan yang ada pada setiap manusia itu alamiah dan manusia harus dikterima dihargai, dan dimengerti apa adanya, kelebihan dan kelemahannya dan juga perbedaannya dengan diri kita.
Asyumardi Asra (2007) dengan sangat menarik menyusun buku tentang multikulturalisme dengan judul Merawat Kemajemukan Merawat
Mengapa jalinan multikulturalisme akhir-akhir ini harus disuarakan lebih lantang? Menurut Asyumardi, sejak jatuhnya Pak Harto pada 1998 terjadi krisis budaya. Di saat itu, muncullah era reformasi yang diikuti oleh masa yang disebut disintegrasi dengan adanya berbagai macam krisis. Apa yang disebut Asyumardi dengan “jalinan tenunan masyarakat” (fabric of society) tercabik-cabik akibat dari krisis berbagai hal dan terlebih adalah krisis budaya. Eforia kebebasan menyebabkan disintegrasi bidang social politik yang sangat luas. Eforia kebebasan meluas, sehingga muncullah aksi-aksi anrkhis di kalangan masyarakat dan sangat berpengaruh kepada menurunnya etika, moral, kepatuhan kepada hokum, sopan santun pergaulan, keberadaban antar sesame, dan juga merosotnya saling penghargaan antaretnis dan agama berupa konflik yang bersifat berkepanjangan di berbagai daerah, pulau, atau antarpulau (2007:7). Dengan kkrisis budaya tersebut, saling penghargaan, toleransi, pemahaman, dan pengertian budaya dari bangsa yang majemuk ini merosot sekali. Egosentrisme kesukuan dankedaerahan muncul dan membesar, istimewa setelah desentralisasi politik dan pemerintahan.
Proses globalisasi dan penetrasi budaya kapitalisme yang mau tidak mau harus masuk ke Indonesia, sedikit banyak menambah kemelut suramnya kerukunan dalammasyarakat majemuk. Budaya Barat yang serba instant, hedonistis, kapitalistis, dan konsumerialistis oleh Asyumardi disebut cultural imperialism menggantikan imperialisme lama yang bersifat orientalisme.
Pada Era Orde Baru, kehidupan multikulturalisme tercipta dengan system pemerintahan sentral dan Demokrasi Pancasila yang ketat. Tentulah tidak bijaksana jika kita menoleh ke masa lalu yang juga memiliki cacat fundamental dalam kehidupan majemuk bangsa karena banyaknya manipulasi kekuasaan dan pemaksaan kehendak yang pada gilirannya pasti berakibat pada tumbangnya kekuasaan itu. Di era kini, saat kondisi multikulturalisme menurun, perlu usaha gigih dari berbagai pihak untuk memupuk multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Perkembangan Sastra
Sejak kelahirannya pada Zaman Balai Pustaka (1920), Sastra
Dalam memperkenalkan budaya,masyarakat, dan adapt istiadat etnis, agama, suku, atau budayanya, sastrawan mengungkapnya dengan penuh kejujuran yang memungkinkan di satu pihak hal-hal yang negative dari etnisnya sendiri disikapi secara objektif, di pihak lain, etnis lainnya berusaha memahami, mengerti, dan menghargai hal yang berbeda dari etnis lain.
1. Puisi
Nafas kebangsaan dan multikulturalisme tercermin dalam puisi-puisi sejak Muhammad Yamin sampai dengan Sutardji Calzoum Bachri. Muhammad Yamin seorang nasionalis yang wafat saat masih menjabat Menteri Depernas (pada Era Bung Karno) sangat rindu persatuan
Sutan Takdir Alisyahbana berdendang tentang
………………………………
Gemuruh berderau kami jatuh
terhempas berderai mutiara bercahaya
Gegap gempita suara mengerang
dahsyat bahasa suara mengerang.
Keluh dan gegak silih berganti
Pekik-pekik sambut-menyambut.
Kami telah menuju ke laut
tasik yang tenang tiada beriak
diteduhi gunung yang rimbun
dari angina dan topan
Sebab sekali kami terbangun
Dari mimpi yang nikmat.
(Waluyo: 247)
Meskipun masih muda, Chairil Anwar memahami usia tua orang lain. Ia juga harus dihargai. Semua orang juga akan menjadi tua. Di saat tua itu, segala piranti dalam kehidupan kita sudah uzur, sudah loyo, sudah rapuh. Karena itu, sesudah tua, setiap orang siap untuk meninggalkan dunia yang fana ini.
DERAI-DERAI CEMARA
Cemara menderai sampai jauh
terasa hari akan jadi malam
ada beberapa dahan merapuh
dipukul angina yang terpendam
aku sekarang orangnya bias tahan
sudah beberapa waktu bukan kanak lagi
tapi dulu memang ada suatu bahan
yang bukan dasar perhitungan kini.
hidup hanya menunda kekalahan
tambah terasing dari cinta sekolah rendh
dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan
sebelum pada akhirnya kita menyerah.
Chailril Anwar, 1979
Bagi Rendra, kehidupan orang-orang papa yang tidak memperoleh kesejahteraan hidup yang memadai harus diperhatikan. Orang-orang papa itu, oleh Rendra disebut orang-orang tercinta, seperti: ibu tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, perawan tua, wanita-wanita kesepian, para pelacur, perampok Atmo Karpo, wanita yangmenderita akibat difitnah (Sumilah), dan juga nabi yang disiksa oleh warga desanya. Berikut disampaikan “Nyanyian Angsa” yang menunjukkan solidaritasnya kepada pelacur yang sekarat tetapi ditolak oleh pejabat agama.
NYANYIAN ANGSA
…………………………………..
(Malaikat penjaga firdaus
wajahnya tegas dan dengki
dengan pedang yang bernyala
menuding kepadaku
Maka darahku terus beku
Maria Zaetun namaku
Pelacur yang sengsara
Kurang cantik dan agak tua)
…………………………………
Jam empat siang
Seperti siput, Maria Zaetun berjalan
Kerigatnya bercucuran
Rambutnya jadi tipis
Makanya kurus dan hijau
Seperti jeruk yang kering
Lalu jam lima
Ia sampai diluar kota
Jalan tak lagi beraspal
Tapi debu melulu
Ia memandang matahari
Dan pelan berkata:”bedebah”.
Sesudah berjalan satu kilo lagi
Ia tinggalkan jalan raya
Dan berbelok masuk sawah
Berjalan di pematang.
…………………………………
Setelah selesai, lelaki itu berkata
“semula kusangka hanya impian
Bahwa lelaki tampan bagai kau
Bakal lewat dalam hidupku”
Lelaki itu tersenyum dengan hormat dan sabar
“Siapakah namamu ?” Maria Zaetun berkata
“Mempelai !” Jawabnya
“Lihatlah engkau melucu !” kata Maria Zaetun
Maria Zaetum menciumi seluruh tubuh lelaki itu
Tiba-tiba ia terhenti
ia jumpai luka-luka pada tubuh pahlawannya
di lambung kiri
di dua tapak tangan
di dua tapak kaki
Maria Zaetun pelan berkata:
“Aku tahu siapa kamu !”
(Malaikat penjaga Firdaus
wajahnya jahat dan dengki
dengan pedang yang menyala
tidak bias apa-apa
aku tak takut lagi
sepi dan duka telah sirna
sambil menari kumasuki taman firdaus
dan kumakan apel sepuasku
Maria Zaetun namaku
Pelacur dan pengantin adalah aku.
(Blues untuk Bonnie, 1972)
Orang yang menderita dan papa seperti Maria Zaetun harus mendapatkan perhatian. Di akhirat (Taman Firdaus) ia diterima sebagai pengantin. Mestinya, di dunia ia tidak disepak dan ditendang seperti anjing.
Taufiq Ismail yang dikenal sebagai penyair demonstrans menyadari benar keindonesiaan dirinya yang merasa bahwa timbul penyimpangan dalampemerintahan selama Rezim Orde Lama. Ia menulis berikut untuk menyadarkan keindonesiaan kita bersama sebagai bangsa yang tidak rela kebersamaan kita diinjak-injak oleh kekuasaan yang bersifat “tirani”. Puisinya yang berjudul “Berikan Indonesiaku Padaku” menunjukkan cinta bangsa dan tanah air dari Taufiq Ismail sebagai bangsa Indonesia.
Dalam Ayat-ayat Api Sapardi Djoko Damono menunjukkan caranya tersendiri dalam mengajak pembacanya untuk mengutuk para pembakar
AYAT-AYAT API
sore itu akhirnya ia berubah juga
menjadi abu sepenuhnya
sbelum sempat menyadari
bahwa ada saat untuk istirahat
di antara gundukan-gundukan
yang sulit dipilah-pilahkan
nah, untuk apa pula
toh segera diterbangkan anginnya selagi hangat
di akhir isian panjang itu
tertera pertanyaan
“apa yang masih tersisa dari tubuhmu”
isi saja “tak ada”
tapi, o, ya, mungkin kenangan
yang tentu juga sia-sia bertahan
waktu upacara hamper usai kau tak ingat
bahwa kuburan di kampong sudah penuh
mungkin satu-satunya basa-basi yang tersisa
adalah menguburmu sementara dalam ingatan kami.
(1998)
Dalam pembahasan tentang multikulturalisme di depab telah dinyatakan bahwa ada aneka ragam perbedaan yang harus ditoleransi. Banyak penyair yang memiliki solidaritas kuat terhadap para penderita, mengutuk keraskorupsi karena mengangakan jurang yang ada antara si miskin dan si kaya, dan juga saling pemahaman antara perbedaan desa kota, Jawa luar Jawa, beda agama, dan segala jenis perbedaan yang ada. Dalam perkembangannya, puisi
2. Prosa Fiksi
Penggambaran secara jujur adapt istiadat dan budaya etnis tertentu oleh para pengarang akan menciptakan saling pengertian budaya denganpembacanya di seluruh
Roman-roman pada Periode Balai Pustaka pada hakikatnya didominasi oleh suasana budaya, adapt, dan suasana sosiologis masyarakat Minangkabau yang matrilineal. Namun di samping itu, sebenarnya dalam suasana masyarakat priyayi, sama saja antara priyayi Jawa dan priyayi Minangkabau. Keluarga Sitti Nurbaya dan Syamsulbachri pada hakikatnya adalah keluarga priyayi Minangkabau. Perhatikan kendaraan, cara berpakaian, dan
Pada Periode Balai Pustaka hanya ada sedikit pengarang roman dari Jawa, antara lain Sutomo Jauhar Arifin. Jika ada persamaan problem tentang kawin paksa dapat dipahami jika ada persamaan juga siapa yang memaksa. Di Jawa yang memaksa adalah keluarga dengan dasar priyayi yang berpedoman bobot, bibit, dan bebet yang pada hakikatnya sifat kepriyayaian Jawa itu sama dengan ninik mamak di Minangkabau. Mungkin, lebih lanjut muaranya juga sama dengan problem masa kini, yaitu masalah harta benda atau kekayaan. Pembaca dari etnis Jawa dan Minang tentunya memiliki cara pandang yang dapat saling dijadikan materi diskusi sehingga menciptakan saling pengertian, penghargaan, dan toleransi.
Roman pembaharu di periode Balai Pustaka seperti Salah Asuhan, dalam Periode Pujangga Baru seperti Belenggu, dalam Periode Angkatan 45 seperti Atheis dapat dikatakan sebagai roman-roman yang tidak lagi memiliki unsure kedaerahan, namun sudah lebih bersifat universal.
Pembaca alim kebanyakan tidak senang kepada prosawan-prosawan seperti Jenar Mahesa Ayu, Ayu Utami, dan Fira Basuki karena pemikiran-pemikirannya tentang hubungan seksualitas yang dipandang “terlalu maju”. Mereka mencoba merenungkan eksistensi wanita menurut perspektif berpikirnya sebagai wanita cosmopolitan yang mengalami kehidupan manusia modern yang sangat beraneka ragam. Kehidupan yang direnungkan belum tentu kehidupannya sendiri, namun bias jadi kehidupan tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat modern yang ingin disampaikan jeritan atau pikirannya itu. Karena sangat geramnya kepada novel-novel mereka bertiga ini, sampai-sampai ada pakar sastra yang menyebut novel mereka adalah novel selangkangan atau novel perlendiran. Padahal dalam novel kita berbicara tidak hanya fisik, namun juga batin manusia, kemungkinan-kemungkinan yang diberikan, pemikiran tentang pembaharuan yang diberikan, dan jalan keluar terhadap keruwetan hidup menghadapi perbedaan perlakuan antarapria dengan wanita, dan sebagainya.
Abidah el Kaliqi dan Andre Hirata boleh dikatakan mampu menghentikan laju diskusi perlendiran dalam novel itu. Apa yang dikemukakan oleh Abidah dalam Perempuan Berkalung Sorban adalah alternatif pemikiran tentang pembaharuan di kalangan pondok pesantren tradisional yang diobservasinya di daerah Magelang. Namun, mungkin apa yang dipandang wajar oleh Abidah, oleh tokoh-tokoh setempat yang diobservasi bernada berlebihan. Begitu juga kepahlawanan bocah-bocah dari Pulau Belitong yang digambarkan oleh Andre Hirata kiranya dapat disebut berlebihan oleh tokoh di luar Belitong, namun oleh suku bangsa Melayu Belitong mungkin merupakan hal yang wajar saja. Namun kedua pengarang yang bukunya sangat laris ini telah menyajikan dunia yang beda melalui karya sastra ke depan khasanah pembaca
Masih dapat dikemukakan contoh-contoh lain yang akan mendukung gagasan yang menyatakan bahwa prosa fiksi dapat menyebarluaskan pemahaman dan penghargaan antar etnis, agama, budaya, kebiasaan, perbedaan status social, perbedaan gender, dan perbedaan bahasa kea rah tolerasni dan saling menghargai dalam kebhinekaan yang bersatu.
Karya dari Manado (Raumanen), Kalimantan (Upacara oleh Korie Layun Rampan), Sulawesi Selatan (Pembayaran oleh Sinansari Ecip), Bali (Tarian Bumi oleh Oka Rusmini), Nusa Tenggara Timur (Sang Guru karya Gerson Poyk), Kalimantan (Tuyet karya Bur Rasuanto), Jawa Tengah (Umar Kayam dan Arswendo Atmowiloto yang menunjukkan masyarakat priyayi; Ahmad Tohari menunjukkan masyarakat santri; Kunto Wijoyo dan Muhammad Diponegoro menunjukkan kelompok masyarakat sastri kota). Karya pengarang dari Jawa itu, misalnya: Para Priyayi, Canting, Satinah dan Wasripin, Ronggeng Dukuh Paruk, dan Mantra Pejinak Ular.Pengarang dari Jawa Barat (Sunda) antara lain: Ramadhan K.H. dengan karyanya Royan Revolusi; dari Irian (Papua) antara lain Dewi Linggarjati (karyanya Sali Kisah Seorang Wanita Suku Dani), Ircham Mahfoedz (karyanya Ratu Lembah Baliem), Don Richardson (karyanya Anak Perdamaian).
3. Drama
Teks drama yang ada dalam khasanan sastra Indonesia berupa dialog. Jika dalam prosa fiksi dialog hanya selingan, maka dalam drama, keseluruhan karya itu adalah berwujud dialog. Dalamdialog ini banyak kita jumpai istilah-istilah bahasa daerah yang sulit diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam pementasannya pun, dramawan sering menggunakan logat berdialog dengan dialek bahasa daerahnya. Hal ini meskipun mempersulit penonton dari etnis lain, namun menambah apresiasi kepada drama dari etnis yang berbeda. Karya-karya Wisran Hadi (kental dengan warna Minang), Suyatna Anirun (kental dengan warna Sunda), karya Arifin C.Noer dan Riantiarno (kuat pengaruh tarling di Cirebon), karya Heru Kesowo Murti (sangat terpengaruh oleh dagelan Mataram dengan logat Jawa Tengah yang kental), Hanindawan (terpengaruh ketoprak dan dagelan dengan logat Jawa Tengah Solo), dan Akhudiat (dengan logat Jawa Timur dan pengaruh kentrung yang cukup kental).
Rendra banyak membawa drama Yunani dan Eropa yang mengajak penonton merenungkankemanusiaan yang universal. Penderitaan dan perbedaan manusia hendaknya tidak menjadi halangan untuk kehidupan damai di muka bumi. Itulah kunci kebahagiaan. Meskipun tokoh yang digambarkan adalah raja-raja yang seharusnya bahagia, namun kenyataannya merekamenderita (Oedipus, Hamlet, Machbeth, Panembahan Reso, Pangeran Homburg). Tingginya kedudukan tidak menjamin kebahagiaan, sebaliknya orang yang berpangkat rendah mungkin memiliki banyak probabilitas untuk bahagia. Di samping karya-karya terjemahan, Rendra masih mencari alternative-alternatif untuk mengajak penonton atau pembaca menghargai martabat manusia tanpa embel-embel kebesarannya.
Drama-drama Indonesia (seperti halnya prosa fiksi) bercerita tentang manusia. Untuk memahami manusia, melalui drama akan dipotret manusia lengkap dengan watak dan tingkah lakunya. Pantas kita sampaikan dramawan-dramawan lain yang perlu disebutkan dalam khasanah sastra Indonesia yang turut memasyarakatkan multikulturalisme adalah: Putu Wijaya, Teguh Karya, Jim Lim, Azwar A.N., Usmar Ismail, Taufiq Ismail, Adi Kurdi, dan Ratna Sarumpaet .
D. Wasana Kata
Baik puisi, prosa fiksi, dan drama menuebarkan gagasan multikulturalisme ke siding masyarakat pembaca atau penonton. Namun, penyebarluasan itu harus dibantu dengan penayangan di televisi atau media
Perlu dicetak dan disebarluaskan buku-buku puisi, prosa fiksi, dan drama yang ditulis oleh berbagai etnis yang ada, berbagai profesi, berbagai tema tentang kesadaran berbangsa dalamkemajemukan, sehingga cita-cita kita tidak kandas oleh perpecahan bangsa.
Guru bahasa
DAFTAR PUSTAKA
Ainul Yaqin. 2005. Pendidikan Multikultualisme. Yogyakarta: Pilar media.
Asyumardi Asra. 2007. Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia. Jogjakarta: Kanisius
Dewi Linggardani. 2007. Sali. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
Don Richardson. 1974. Anak Perdamaian. Bandung: Kalam Hidup.
Herman J.Waluyo. 2007. Pengkajian Puisi. Salatiga: Widyasari.
_______________. 2008. Pengkajian Prosa Fiksi. Salatiga: Widyasari.
_______________. 2007. Drama dan Pengajarannya. Surakarta: UNS-Press.
Ircham Mahfoedz. 2002.Ratu Lembah Baliem.Yogyakarta: Gita Nagari.
Modood, Tariq. 2009. Multiculturalism. http://www.answer.com/topic/multiculturalism. diunduh 13 Desember 2009.
Sapardi Djoko Damono. 2000. Ayat-ayat Api. Jakarta: Pustaka Firdaus.